Ikhbar.com: Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera bukanlah peristiwa biasa. Air datang membawa lumpur dan kerusakan, sekaligus menguji kesiapan manusia dalam membaca risiko. Ratusan korban kehilangan nyawa, ribuan warga terpaksa mengungsi. Rumah, sekolah, serta fasilitas umum mengalami kerusakan. Jalur transportasi terputus, sementara jaringan listrik lumpuh.
Dalam situasi darurat tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana manusia sungguh-sungguh belajar dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan bencana?
Pertanyaan tersebut telah lama hadir dalam peradaban Islam. Sejarah menunjukkan bahwa bencana alam tidak dipahami sebagai musibah yang diterima dengan sikap pasrah. Peristiwa semacam ini dipandang sebagai sesuatu yang menuntut pembacaan cermat, pengetahuan memadai, dan tanggung jawab nyata. Dari perspektif inilah berkembang ilmu pengetahuan, kebijakan publik, serta etika sosial yang bertumpu pada pengalaman empiris dan nalar praktis.
Jauh sebelum istilah mitigasi dan tata kelola bencana dikenal dalam bahasa modern, ilmuwan Muslim, navigator, arsitek, dan ahli fikih telah berupaya memahami alam sebagai sistem yang memiliki pola dan isyarat. Alam diamati dan direspons sebagai realitas yang harus dipahami, bukan sebagai sumber ketakutan tanpa dasar.
Peneliti sejarah sains Islam asal Arab Saudi, Lutfallah Gari, menegaskan bahwa pada abad ke-15 dan 16, periode yang kerap dipahami sebagai kelanjutan Renaisans Islam, telah lahir karya-karya berbahasa Arab yang secara khusus membahas topan laut dan gempa bumi.
“Di dalam naskah-naskah tersebut, bencana tidak ditempatkan sebagai kehendak langit yang berada di luar jangkauan manusia, tetapi sebagai peristiwa alam yang meminta kecermatan, keputusan teknis, serta tanggung jawab kolektif,” tulisnya dalam Knowledge versus Natural Disasters from Arabic Sources (2008) di Muslim Heritage, dikutip pada Selasa, 2 Desember 2025.
Baca: Pengendalian Banjir di Masa Kekhalifahan Islam
Seni membaca alam
Dalam tradisi Islam klasik, pengenalan gejala alam menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kehidupan. Literatur Arab pra-Islam mencatat hampir seratus istilah untuk berbagai jenis angin yang dibedakan berdasarkan arah, kekuatan, suhu, dan dampak. Kekayaan bahasa tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan pengetahuan meteorologi di dunia Islam.
Sejak abad ke-9, setelah karya-karya Yunani diterjemahkan, ilmuwan Muslim mengembangkan teori alam berbasis rasionalitas. Al-Kindī menjelaskan angin sebagai akibat pergerakan udara panas menuju wilayah yang lebih dingin dan padat. Gagasan ini kemudian diperkaya oleh Al-Tīfāshī dan al-Qazwīnī yang memaparkan badai dan angin topan sebagai pusaran udara bertekanan tinggi di atmosfer.
“Untuk konteks zamannya, deskripsi ini menunjukkan keberanian berpikir ilmiah yang melampaui mitos,” tulis Gari.
Pengetahuan tersebut tidak berhenti sebagai wacana teoretis. Dalam dunia pelayaran, pemahaman ini menjadi penentu keselamatan. Ibn Mājid, navigator Samudra Hindia abad ke-15, menuliskan tanda-tanda datangnya taifun secara rinci. Suhu air laut yang menghangat, hujan lebat, perubahan arah angin mendadak, kilat, pusaran air, sampai awan yang digambarkan terkelupas seperti kulit sapi menjadi sinyal penting bagi para pelaut.
Navigator lain, Sulaymān al-Mahrī dari Sukotra, mengklasifikasikan lima jenis taifun di Samudra Hindia beserta waktu kemunculan dan wilayah rawannya. Ia menegaskan bahwa topan memang tidak terjadi setiap tahun, namun selalu didahului gejala yang dapat dikenali oleh pengalaman dan ketelitian.
“Bencana dipahami bukan sebagai peristiwa yang datang secara mendadak. Yang sering absen, justru kepekaan manusia,” katanya.
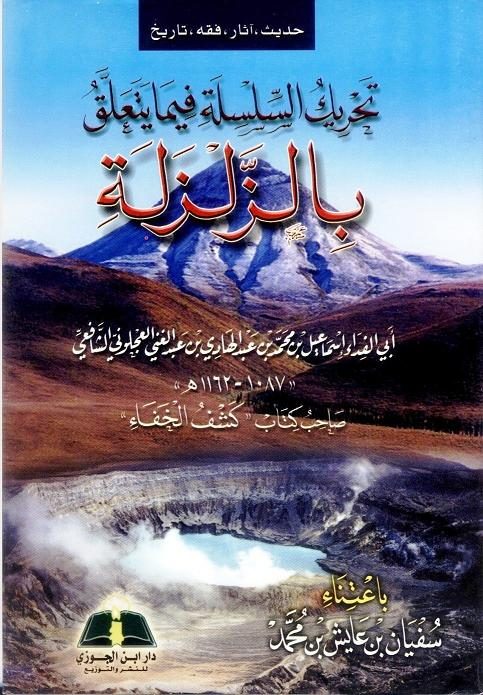
Baca: Beda Makna Musibah, Cobaan, dan Azab dalam Al-Qur’an
Pencegahan sebagai prinsip
Kesadaran terhadap risiko alam diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Dalam sektor maritim, pembangunan kapal berada di bawah pengawasan muhtasib, pejabat negara yang bertugas memastikan standar teknis dijalankan. Kapal tidak diperkenankan dibuat dari bahan bermutu rendah atau menyimpan cacat tersembunyi karena dampaknya menyangkut keselamatan manusia.
Ibn Mājid menekankan bahwa seluruh bagian kapal harus diperiksa sejak proses pembangunan di darat, dan setiap kerusakan dicatat secara terbuka. Selama pelayaran, peralatan wajib melewati pemeriksaan berkala. Ibn Bassām merumuskan tujuan pengawasan ini dengan tegas, yakni mencegah hilangnya nyawa dan harta benda.
Muatan berlebih dipandang sebagai pelanggaran serius dengan ukuran yang jelas. Selama garis air masih tampak di lambung kapal, muatan dinilai aman. Apabila kapal tenggelam akibat pelanggaran tersebut, tanggung jawab hukum dibebankan kepada manusia, baik kapten, penyewa, maupun pemilik kapal. Takdir tidak digunakan sebagai pembenaran atas kelalaian.
Dalam kondisi darurat, pilihan rasional sering kali mengarah pada langkah mundur. Catatan tahun 1518 menunjukkan kapal-kapal yang hendak berlayar dari Alexandria menuju Istanbul memilih kembali ke Pelabuhan Rosetta ketika badai mendekat. Dalam tradisi ini, keselamatan ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan dagang.
Baca: Kualitas Hablum Minal Alam Tentukan Keberadaan Bencana
Pengalaman kolektif dan budaya siaga
Gempa bumi menjadi jenis bencana lain yang banyak dicatat dalam sumber Islam klasik. Sejak awal, ilmuwan seperti Ibn Sīnā membahas gempa sebagai fenomena fisik. Tekanan gas di dalam bumi, runtuhan tanah, masuknya air, serta perubahan suhu ekstrem disebut sebagai pemicu utama.
Pada abad ke-15, al-Suyūtī menyusun risalah yang mencatat lebih dari 130 peristiwa gempa di berbagai wilayah Muslim. Kendati ditafsirkan sebagai peringatan ilahi, murid-muridnya memperkaya naskah tersebut dengan data empiris berupa tanggal kejadian, lokasi, durasi, serta dampak terhadap kota dan permukiman.
Kronik sejarah memperlihatkan pola respons sosial yang konsisten. Ketika gempa terjadi atau kabarnya menyebar, warga meninggalkan rumah dan membangun tempat berlindung di ruang terbuka. Di Granada, Damaskus, Yaman, hingga Zayla‘, masyarakat bertahan di tenda selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sembari menunggu gempa susulan berakhir. Di wilayah rawan gempa, gubuk kayu sengaja didirikan di samping rumah sebagai perlindungan darurat pada malam hari.
Praktik tersebut tidak mencerminkan kepanikan massal, melainkan kebiasaan yang dibentuk oleh pengalaman panjang. Sejarah menunjukkan lahirnya budaya kebencanaan sebagai pola hidup waspada di tengah risiko alam yang terus hadir.

Baca: Hukum Salat dan Tutorial Wudu di Tengah Bencana Banjir
Fikih yang berpihak pada keselamatan
Sikap rasional tersebut memperoleh legitimasi kuat dalam hukum Islam. Ulama menegaskan bahwa perlindungan jiwa menempati posisi utama dalam syariat. Al-Nawawī, ulama besar mazhab Syafi’i, memasukkan gempa ke dalam kategori salat khauf, yaitu keadaan genting yang menghadirkan keringanan dari kewajiban salat berjemaah.
Umat dianjurkan menjauhi bangunan berbahaya serta tidak bertahan di lokasi yang mengancam keselamatan dengan alasan formalitas ibadah.
“Agama tampil sebagai sistem etika yang melindungi manusia, bukan menambah beban di tengah krisis,” tulis Gari.
Sejarah Islam, sebagaimana tercermin dalam naskah-naskah tersebut, memperlihatkan wajah agama yang rasional, preventif, dan bertumpu pada tanggung jawab sosial. Dalam konteks hari ini, banjir besar yang melanda Sumatera patut dibaca sebagai peringatan keras. Bencana tidak berhenti pada tuntutan empati setelah air surut, melainkan menuntut kesiapan yang dibangun jauh sebelum hujan pertama turun.















