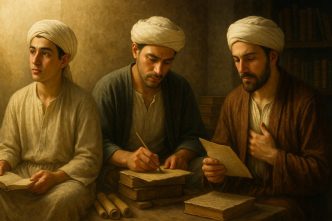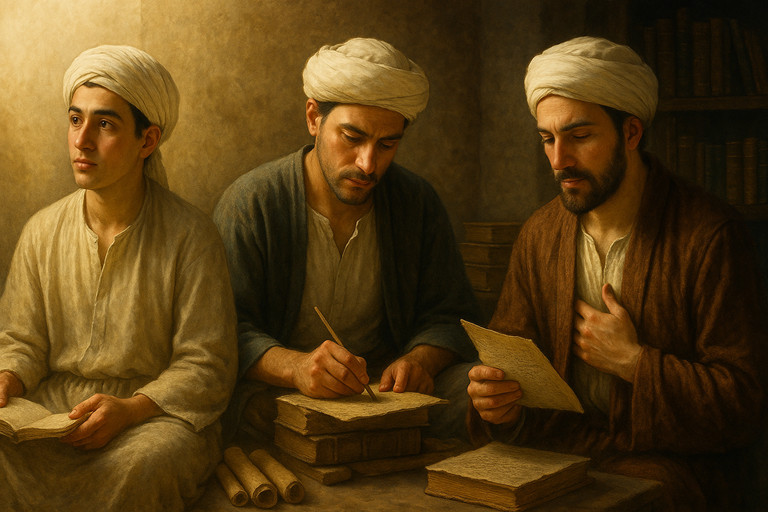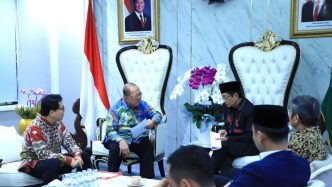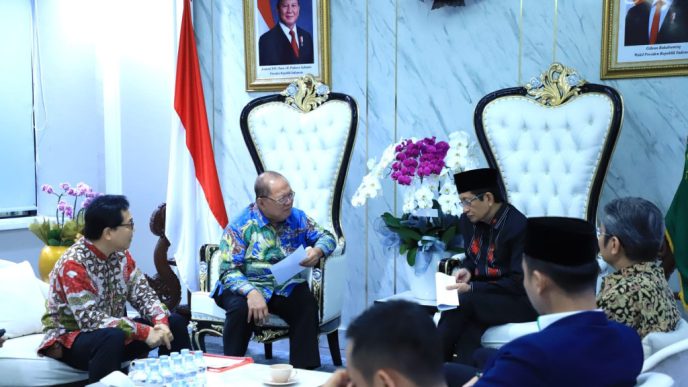Ikhbar.com: Bulan Juni kerap disambut dengan antusiasme tinggi para pelajar dalam menyongsong kelas atau jenjang baru. Hal ihwal terkait sekolah pun ramai kembali, mulai dari aktivitas orang tua memenuhi persyaratan daftar ulang, menjahit seragam, membeli buku dan peralatan seperti sepatu, tas, dan sejenisnya. Semua sibuk bersiap menghadapi awal yang baru, penuh harapan dan tantangan.
Meskipun tak sama, antusiasme ini sejatinya sejalan dengan teladan para ulama terdahulu yang menempatkan semangat sebagai fondasi utama dalam belajar meski harus menghadapi keterbatasan sarana. Sosok seperti Abdullah bin Abbas Ra, Imam Syafi’i, dan Imam Al-Ghazali menjadi contoh nyata kegigihan dan ketekunan dalam menuntut ilmu.
Baca: Beda Makna ‘Ilmu’ dalam Kamus Islam dan Barat
Ibnu ‘Abbas, sabar dan rendah hati
Salah satu tokoh yang menjadi panutan dalam ketekunan menuntut ilmu adalah sepupu sekaligus sahabat Nabi Muhammad Saw, Abdullah bin Abbas Ra.
Dalam Al-Mu’jam al-Kabir, Imam At-Thabrani mencatat bahwa Ibnu Abbas rela menunggu di depan rumah seorang guru ketika sang ustaz tengah tidur siang. Ketika yang ditunggunya itu menawarkan untuk datang ke rumah Ibnu ‘Abbas karena merasa sungkan, Ibnu Abbas justru menolak dan menegaskan bahwa dialah yang berkewajiban mendatangi ilmu, bukan sebaliknya.
Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Al-A’lam an-Nubala’ menggambarkan Ibnu ‘Abbas sebagai bahrul ‘ilmi (lautan ilmu) dan ra’isul mufassirin (pemuka para ahli tafsir) pada zamannya. Sementara ulama lain menyebutnya sebagai turjuman Al-Qur’an (penafsir al-Quran), dan habrul ummah (guru umat).
Ibnu Abbas seakan tidak puas hanya mendengar hadis dari satu orang, melainkan menanyakannya kembali kepada puluhan sahabat untuk memastikan keabsahannya. Ia pun mendorong murid-muridnya mencatat hadis agar ilmu tidak hilang begitu saja.
Ketokohan Ibnu Abbas juga tercermin dalam karya-karya tafsir yang dinisbatkan kepadanya. Dua yang paling dikenal adalah Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas karya Abu Thahir al-Fairuz Abadi, dan Tafsir Ibn ‘Abbas al-Musamma Shahifah ‘Ali bin Abi Thalhah.
Baca: Reformasi Fikih ala Imam Syafi’i
Kreativitas Imam Syafi’i
Keteladanan lainnya datang dari Imam Syafi’i. Ulama besar pendiri salah satu mazhab fikih ini berasal dari keluarga sederhana.
Dalam Manaqib Asy-Syafi’i, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut bahwa Imam Syafi’i tak memiliki cukup uang untuk membeli kertas. Ia pun mencatat pelajaran di atas tulang belulang, pelepah kurma, dan bahan-bahan lain yang bisa digunakan untuk menulis.
Bagi Imam Syafi’i, keterbatasan justru memicu kreativitas dan tidak menjadi penghalang dalam menggapai ilmu.
Dalam Thabaqat as-Syafi‘iyyin, Ibn Katsir menyatakan bahwa Imam Syafi’i telah menghafal Al-Qur’an pada usia tujuh tahun, dan pada usia 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Muwaththa’ karya Imam Malik.
Imam Syafi’i berguru kepada banyak ulama di berbagai wilayah, dari Makkah hingga Yaman. Waktu yang panjang dan jarak tempuh yang jauh itu menunjukkan totalitasnya dalam menuntut ilmu.
Imam Adz-Dzahabi juga mencatat perjalanan intelektual Imam Syafi’i. Di Makkah, ia belajar kepada para ulama besar seperti Muslim bin Khalid az-Zanji (mufti Makkah), Sufyan bin ‘Uyainah, dan Fudhail bin ‘Iyadh.
Di usia dua puluhan, ia sudah memberikan fatwa, lalu melanjutkan studi ke Madinah dan berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, dengan menghafal Al-Muwaththa’.
Di Yaman, Imam Syafi’i berguru kepada para ahli fikih seperti Hasyim bin Yusuf. Di Baghdad, ia mendalami fikih Hanafi dari Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Usai proses belajarnya, Imam Syafi’i membawa pulang satu kafilah unta penuh kitab.
Imam Al-Ghazali, menyeimbangkan intelektual dan spiritual
Ketekunan luar biasa juga ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali. Ulama yang bergelar Hujjatul Islam itu dikenal menguasai multi-disiplin ilmu. Kepakarannya meliputi ilmu fikih, ushul, kalam (teologi), tasawuf, hingga filsafat.
Ia memulai belajar sejak kecil di tanah kelahirannya, Thus, Iran, bersama Syekh Ahmad Ar-Radhkani, lalu melanjutkan ke Jurjan untuk berguru kepada Syekh Al-Isma‘ili.
Abdul Karim Utsman dalam Sirah al-Ghazali menceritakan kisah yang membekas bagi diri Al-Ghazali. Dalam perjalanan pulang ke Thus, ia dirampok dan seluruh catatan ilmunya diambil. Namun ia memohon kepada perampok untuk mengembalikan catatannya, tetapi sang pemimpin perampok berkata:
“Bagaimana mungkin engkau mengaku telah mengetahui ilmunya, sementara ketika kami mengambilnya, engkau merasa tak lagi memilikinya?”
Ucapan itu menggugah Al-Ghazali, sehingga ia menghafal ulang seluruh catatannya selama tiga tahun tanpa lengah.
Syekh Tajuddin As-Subki dalam Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra mencatat bahwa selepas menimba ilmu di Jurjan, Al-Ghazali melanjutkan studi ke Naisabur, Iran, dan berguru kepada Imam Al-Haramayn Al-Juwayni, yakni ulama besar mazhab Syafi‘i dan kepala Madrasah Nizamiyyah.
Di sana ia mempelajari fikih mazhab, ushul fikih, kalam, logika, dan filsafat. Imam Al-Juwayni memuji Al-Ghazali sebagai “lautan yang memancar.”
Setelah wafatnya Imam Al-Juwayni, Al-Ghazali pergi menuju ʿAskar untuk menghadap Wazir Nizham Al-Mulk. Wazir sangat terkesan setelah menyaksikan kepiawaian Al-Ghazali dalam debat dengan para ulama, dan mengangkatnya sebagai pengajar di Madrasah Nizhamiyyah Baghdad pada usia 30 tahun.
Di Baghdad namanya semakin berkibar, hingga dikenal sebagai Imam Al-ʿIraq, selain Imam Khurasan. Pada masa ini, ia banyak menulis karya dalam bidang fikih, ushul, kalam, dan filsafat hikmah.
Namun, di puncak ketenarannya, Al-Ghazali mengalami krisis batin. Ia merasa kosong secara spiritual dan merasakan kehausan akan hakikat.
Dalam kegelisahan itu, ia bertemu dengan seorang sufi, Abu ʿAli Al-Faramidhi. Melalui bimbingannya, Al-Ghazali melatih diri dalam ibadah lahir dan batin seperti salat sunnah, zikir, dan mujahadah. Ia juga membaca banyak karya tasawuf, seperti Qut Al-Qulub karya Abu Thalib al-Makki.
Spiritualitasnya makin menguat, hingga akhirnya ia meninggalkan Baghdad menuju Makkah dan Madinah, lalu bermukim di Syam (Baitul Maqdis) selama 10 tahun.
Di sana ia berkhalwat, beribadah secara intens, dan menulis sejumlah karya penting, termasuk karya magnum opusnya, Ihyaʾ ʿUlum Ad-Din, dan ringkasan-ringkasannya seperti Al-Arbaʿin, Al-Qisthas al-Mustaqim, dan Mihak an-Nazhar.
Dalam autobiografinya, Al-Munqidh min ad-Dhalal, Al-Ghazali mencatat krisis batin yang ia alami itu mengantarnya pada kesimpulan bahwa ilmu yang tak melahirkan rasa takut dan cinta kepada Tuhan adalah ilmu yang sia-sia.