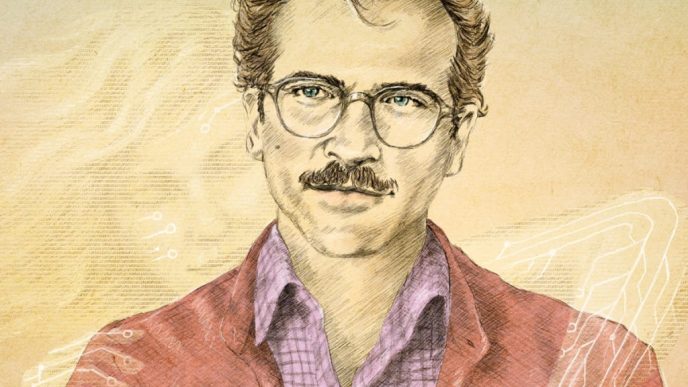Ikhbar.com: Sebuah artikel ilmiah tentang sinyal biologis dalam sel punca sperma mendadak viral bukan karena isi penelitiannya, melainkan gambar tikus dengan penis raksasa dan label ngawur seperti “testtomcels” dan “dck” yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI).
Artikel itu sempat terbit di Frontiers in Cell and Developmental Biology, tetapi ditarik hanya tiga hari kemudian karena gagal lolos peer review (tinjauan sejawat).
Skandal ini menjadi simbol dari persoalan yang lebih besar dalam dunia publikasi akademik.
Jurnal ilmiah telah menjadi penjaga gerbang pengetahuan sejak Philosophical Transactions diterbitkan Royal Society pada 1665. Kini, jutaan makalah baru terbit setiap tahun.
Namun, menurut para ilmuwan terkemuka, sistem ini “rusak” dan “tidak berkelanjutan.” Mantan penasihat sains pemerintah Inggris, Sir Mark Walport, menilai industri ini terlalu berorientasi kuantitas, bukan kualitas.
“Volume adalah indikator yang buruk. Insentifnya seharusnya untuk kualitas,” ujar Walport, dikutip dari The Guardian, pada Senin, 14 Juli 2025.
Baca: Beda Makna ‘Ilmu’ dalam Kamus Islam dan Barat
Analisis Clarivate menunjukkan bahwa jumlah artikel ilmiah di basis data Web of Science meningkat 48% antara 2015 dan 2024, dari 1,71 juta menjadi 2,53 juta. Bila dihitung semua jenis publikasi, angkanya mencapai 3,26 juta per tahun.
Dr. Mark Hanson dari University of Exeter menggambarkan para ilmuwan kini “kewalahan” menghadapi ledakan publikasi dan beban peer review yang mencapai lebih dari 100 juta jam kerja secara global pada 2020, setara dengan Rp24,6 triliun waktu kerja gratis di Amerika Serikat (AS) saja.
Hanson juga menyoroti insentif yang mendorong peneliti mengejar jumlah publikasi demi karier, alih-alih mendalami riset bermakna.
“Mereka terdorong untuk memublikasikan sebanyak mungkin, bahkan jika tidak ada hal baru atau berguna di dalamnya,” jelasnya.
Model bisnis jurnal ilmiah pun dikritik. Para ilmuwan melakukan riset yang dibiayai pajak, menulis dan mereview makalah secara sukarela, sementara penerbit komersial memungut biaya tinggi. Untuk akses terbuka, penulis bisa membayar hingga Rp213 juta per artikel.
Data menunjukkan bahwa antara 2015–2018, peneliti global menghabiskan lebih dari Rp16 triliun untuk biaya publikasi di lima penerbit besar: Elsevier, Sage, Springer Nature, Taylor & Francis, dan Wiley.
Model ini mendorong penerbit membuka ribuan edisi khusus untuk mengundang lebih banyak artikel.
Salah satu penerbit, MDPI, melalui International Journal of Molecular Sciences, membuka lebih dari 3.000 edisi khusus dengan biaya Rp55 juta per artikel. Akibat kekhawatiran mutu, Swiss National Science Foundation menolak membiayai publikasi di edisi semacam itu.
Baca: Rahasia ‘Iqra’ di Era Kecerdasan Buatan (AI)
Krisis ini turut diperparah oleh jurnal predator, makalah palsu dari “paper mills,” dan penggunaan AI untuk menulis artikel ilmiah. Bahkan Taylor & Francis menangguhkan sementara pengiriman artikel ke jurnal Bioengineered karena mencurigai manipulasi terhadap 1.000 makalah.
Hanson menyarankan lembaga pendanaan hanya mendukung publikasi di jurnal nirlaba.
Profesor Andre Geim, peraih Nobel dari University of Manchester, mengatakan banyak makalah “tak berguna” dipublikasikan dan komunitas ilmiah terlalu enggan meninggalkan bidang-bidang riset yang tak lagi produktif.
“Setelah mencapai massa kritis, komunitas ilmiah cenderung mempertahankan diri demi kepentingan emosional dan finansial,” ujarnya.
Hannah Hope dari Wellcome Trust menilai peer review tetap penting, tetapi perlu ditinjau efektivitasnya. Ritu Dhand dari Springer Nature membantah tuduhan “penerbit rakus,” dan menekankan bahwa dunia riset kini lebih global, dipimpin oleh Tiongkok, bukan lagi Barat.
Venki Ramakrishnan, mantan presiden Royal Society, menilai peran teknologi bisa jadi solusi masa depan.
“Akhirnya, semua makalah akan ditulis oleh AI dan dibaca serta dirangkum oleh AI lain untuk manusia,” katanya.