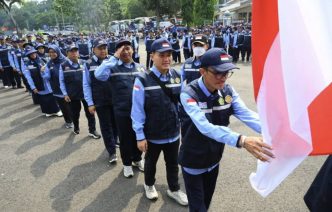Ikhbar.com: Tiga dekade setelah perang Bosnia berakhir, tragedi Srebrenica—pembantaian lebih dari 8.000 lelaki dewasa dan anak-anak Muslim pada 1995—kembali terasa menghantui ketika kekerasan di Gaza meningkat. Dua peneliti asal Bosnia, Samir Beharić dan Emina Zoletić, melihat ironi besar, yakni para ahli genosida dunia, termasuk mereka yang selama ini meneliti pola kebiadaban Srebrenica, justru bungkam saat menyaksikan kehancuran Gaza.
“Diam bukan posisi netral, tetapi pilihan politik yang mempertahankan dampak kejahatan,” tulis keduanya dalam artikel berjudul Why many Bosnian genocide scholars remain silent on Gaza? di Al Jazeera, dikutip pada Selasa, 18 November 2025.
Baca: Terungkap! Buzer Israel Dibayar Rp116 Juta per Postingan TikTok dan Instagram
Perang Bosnia 1992–1995 menewaskan sekitar 100.000 orang dan mencapai puncaknya pada pembunuhan massal oleh pasukan Serbia Bosnia di wilayah yang ditetapkan PBB sebagai “zona aman” tersebut. Setelah perang berakhir, Mahkamah Internasional untuk Bekas Yugoslavia memeriksa ratusan saksi dan menghukum puluhan pejabat politik serta militer. Bosnia dan para donor internasional juga menginvestasikan dana besar untuk penelitian, pemulihan korban, dan peringatan sejarah.
Karena itu, ketika warga Gaza dibombardir, banyak penyintas Bosnia tidak bisa menutup mata. Mereka melihat pola yang serupa: dehumanisasi, mobilisasi ideologi, dan pembiaran dunia internasional. Aksi solidaritas bermunculan di Sarajevo. Namun, banyak akademisi memilih diam.
“Meskipun tidak semuanya. Tetap ada suara lantang. Para profesor seperti Lejla Kreševljaković, Sanela Čekić Bašić, Gorana Mlinarević, hingga Sanela Kapetanović teguh menyatakan tanggung jawab moralnya untuk tidak membisu,” tulis mereka.
Para akademisi tersebut ikut aksi, menyampaikan kritik, dan menekankan pentingnya keberpihakan pada kemanusiaan. Akademisi Belma Buljubašić bahkan menyoroti pemimpin Eropa yang “mengucapkan belasungkawa untuk Srebrenica, tetapi membenarkan tindakan Israel sebagai pertahanan diri”, sebuah standar ganda yang menurutnya “menggerus solidaritas dan akuntabilitas”.
Sarjana genosida Edina Bećirević menilai pola kekerasan di Gaza “jelas mencerminkan dinamika Srebrenica”. Profesor Ahmet Alibašić turut menggelar seminar From the Balkans to Gaza, mengulas persamaan antara pengepungan Sarajevo, genosida Srebrenica, dan kekerasan di Gaza. Banyak jurnalis dan akademisi feminis juga rutin menggelar aksi dengan membaca nama anak-anak Palestina yang terbunuh.
“Namun, diamnya sebagian besar peneliti tetap mencolok. Sejumlah lembaga, termasuk institut penelitian kejahatan kemanusiaan di Universitas Sarajevo, baru bersuara ketika gencatan senjata hampir tercapai. Itu pun tanpa menyebut Israel sebagai pelaku,” ungkap keduanya.
Mereka menyebut sikap menghindar itu sebagai manuver oportunistik.
Baca: PBB: Israel Terbukti Lakukan Genosida di Gaza
Sosok yang paling disorot adalah Emir Suljagić, penyintas genosida dan direktur Pusat Memorial Srebrenica. Ketika ditanya soal Gaza pada akhir 2023, ia menjawab bahwa “itu bukan urusan kami”. Pernyataan ini dianggap bertentangan dengan tulisannya setahun sebelumnya yang mendesak Ukraina untuk tidak menurunkan senjata. Di bawah kepemimpinannya, memorial juga memproduksi studi tentang Ukraina, Suriah, Sudan Selatan, dan Ethiopia, sehingga publik bertanya mengapa Gaza tidak mendapat perhatian yang sama.
“Ketika komunitas Palestina di Bosnia mempertanyakan diamnya institusi tersebut, Suljagić malah menuding mereka anti-Semit. Ia bahkan membandingkan Hamas dengan Chetnik, kelompok ekstremis Serbia yang pernah melakukan pembantaian terhadap Muslim Bosnia,” tulis keduanya.
Beharić dan Zoletić menilai keheningan itu bukan kebetulan. Ada akademisi yang takut kariernya terganggu di kampus-kampus Barat. Ada yang khawatir kehilangan pendanaan dari kedutaan atau donor Eropa–Amerika. Ada pula yang menghindari benturan dengan kepentingan diplomatik tertentu.
Namun, bagi mereka, alasan itu tidak dapat dibenarkan ketika para penelitinya bekerja di institusi yang dibiayai pajak publik.
“Sebagai peneliti genosida yang dibiayai rakyat, tugas mereka adalah menjaga integritas ilmiah dan berbicara berdasarkan bukti,” tegas keduanya.
Ketika ilmuwan memilih diam terhadap kekerasan massal, mereka ikut membangun hierarki korban. Satu tragedi dianggap penting, sementara yang lain diabaikan. Bila dibiarkan, studi genosida berubah menjadi alat politik, bukan disiplin yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Karena itu, Beharić dan Zoletić menyerukan etika baru bagi para intelektual: keberanian untuk berkata jujur, menolak manipulasi kekuasaan, dan berpihak pada prinsip keadilan universal.
“Karena, seperti mereka tekankan, diam bukan absen bicara. Diam adalah keberpihakan,” pungkas mereka.